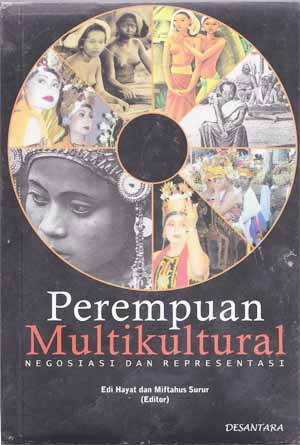Ada pernyataan menarik yang diajukan Melani Budianta saat menulis makalah tentang perempuan subaltern. Siapakah perempuan subaltern? Apakah penyanyi perempuan tradisional yang suara dan gayanya telah mendorong anaknya yang berumur 8 tahun itu, sehingga mengganti chanel yang lebih sesuai dengan seleranya, atau mereka yang dikonseptualisasikan secara abstrak dalam makalah Melani?
Ataukah subaltern adalah pembantu rumah tangganya yang pekerjaannya dan suaranya yang tak terdengar, sehingga telah memberikan kesempatan dan kemewahan bagi Melani untuk menulis makalah?Contoh yang dibuat oleh Melani, tidak saja membuktikan betapa tidak mudahnya melakukan maping terhadap perempuan yang tertindas, tetapi juga persoalan lebih dasar, siapa perempuan subaltern? Menjadi semakin menarik, karena beberapa kalangan juga menyesalkan ‘ideologi pukul rata’ yang dilakukan oleh feminis, yang justru menjadi bentuk baru kolonialisasi perempuan atas perempuan.
Bahwa ada sebagian feminis yang tak melihat persoalan perempuan tanpa melihat geografi, demografi, tingkat pengetahuan serta perkembangan teknologi dan informasi. Semangat gebyah-uyah yang justru dianggap menghilangkan subyek perempuan subaltern dengan segala siasat dan resistensinya.
Menjadi semakin lengkap, saat aliran-aliran feminis global; radikal, liberal, marxist maupun sosialis yang dijadikan acuan, terkadang begitu saja di-breakdown oleh feminis Indonesia. Rumitnya perempuan subaltern inilah yang tampaknya, mencoba dikupas di buku Perempuan Multikultural; Representasi dan Negosiasi. Ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang mencoba disuarakan. Semisal pertanyaan yang dilontarkan oleh Manneka Budiman, saat feminis Kanada menolak pornografi yang dianggap mengeksplorasi perempuan, para artis porno–yang perempuan juga–, berdemonstrasi atas lahirnya UU yang membatasi pekerjaan mereka. Manakah yang harus diprioritaskan? Apakah kaum feminis Kanada atau justru artis pornonya? Atau pertanyaan yang diajukan Donny Gahral Adian tentang, atas dasar apakah penindasan terjadi? Karena jenis kelaminkah? Atau karena ras? Karena Etnis, atau karena kelas?
Jamaknya, feminisme secara konsisten memperjuangkan kesetaraan gender, yang berarti mengubah kultur patriarkhi yang monolitik, menjadi multikultur. Bahwa ada fenomena perempuan ditindas, ada pula keinginan dari feminis untuk melakukan advokasi, sehingga konklusi ini menjadi klop antara agenda feminis yang berarti menghilangkan penindasan yang artinya juga menjadi salah satu komponen dari agenda multikultural. Tetapi ketika kategorisasi itu salah diterapkan, alih-alih memberdayakan, yang terjadi justru bentuk baru imperialisme.
Tulisan yang dibuat oleh Mohanty tentang perempuan Dunia Ketiga cukup tegas memberi gambaran itu. Bahwa gerakan feminis Barat yang niatnya mulia, justru berakibat fatal dengan semakin tertindasnya perempuan Dunia Ketiga setelah sebelumnya ditindas laki-laki dan kapitalisme. Sejurus dengan Mohanty, Ahmad Baso juga menjadikan feminis postkolonial India, Gayatri Chakravorty Spivak sebagai alat untuk merekonstruksi gerakan feminisme yang justru ikut menghakimi perempuan dunia ketiga yang powerless.
Buku ini memang tidak dikhususkan untuk mencari way laut atas beragam problem tadi, tetapi sebagai pelengkap perspektif. Buku ini juga menarik untuk dikaji terutama bagi kaum feminis sehingga lebih arif dalam melihat persoalan terutama tentang perempuan subaltern. Alih-alih keinginan untuk melakukan advokasi, justru menjadi bumerang bagi perempuan subaltern.
Dari titik inilah tampaknya, gerakan feminis harus lebih cerdas untuk menafsirkan kategorisasi tentang perempuan subaltern yang ada di sekitarnya, sehingga, mereka tidak menjadi imperialis baru. Bahwa, dalam setiap hegemoni selalu ada resistensi sebagaimana kata Edward W Said, patut untuk disimak kembali. Desantara
ISBN : 979359601-5
Jumlah Halaman : 308
Editor : Edy Hayat dan Miftahus Surur
Penerbit : Desantara
Tahun Terbit : 2005